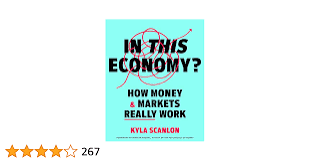Revolusi Mental Oligarki

Oleh: Made Supriatma
Buletinnews– Hari ini, 27 tahun yang lalu, Suharto tumbang. Kekuasaannya yang dibangun di atas pembantaian yang brutal dan ketakutan akhirnya jatuh juga. Krisis ekonomi setahun sebelumnya membuat rejim yang dibangunnya berantakan.
Saya masih ingat suasana itu. Kejatuhan Soeharto didahului oleh berbagai kerusuhan. Pertama adalah kerusuhan anti agama minoritas. Tahun 1995-97 adalah tahun-tahun sulit menjadi penganut agama minoritas. Rumah-rumah ibadah dibakar. Provokasi atas nama agama marak dimana-mana.
Sasarannya adalah agama-agama yang jumlahnya minoritas. Di daerah yang mayoritas Islam, sasarannya adalah rumah ibadah Kristen atau minoritas lainnya. Di daerah yang mayoritas Kristen, sasarannya adalah rumah-rumah ibadah Muslim. Kerusuhan etnis pun berlatar belakang dari sini.
Banyak orang menengarai bahwa kerusuhan-kerusuhan ini memang diorkestrasi (didalangi). Para intelektual dan akademisi berusaha menelisiknya — mengapa sasarannya adalah rumah-rumah ibadah, bahkan yang sudah puluhan ada di tempat-tempat yang dibakar itu?
Saya ingat pernah membaca data kerusuhan itu. Hanya dalam dua tahun itu saja, 900 lebih rumah ibadah dibakar. Sebagian besar adalah gereja. Mengingat jumlah dan besarannya, saya tidak bisa tidak menjadi maklum bahwa ini adalah orkestrasi.
Pertarungan kekuasaan di dalam militer kabarnya membuat kerusuhan ini terjadi. Faksi-faksi di dalam tentara, antara “ABRI merah putih” dan “ABRI hijau” yang berusaha menjadi paling dekat dengan Soeharto, membuat para jendral ini berusaha saling menjatuhkan.
Tapi tetap saja, kita tidak tahu siapa yang membakar dan apa tujuannya. Di negeri ini, hal-hal seperti itu tidak pernah dibahas. Mereka yang bertarung pada tahun-tahun itu malah sekarang mendapat kursi empuk kekuasaan.
Yang kedua adalah krisis ekonomi yang mulai pada 1997. Saya menyebutnya sebagai “food riots.” Ini adalah kerusuhan berbasis ekonomi. Di kota-kota besar dan kecil, kerusuhan terjadi. Rakyat tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Sasaran mereka adalah sesama rakyat yang memiliki toko. Karena para pemilik toko di daerah-daerah adalah minoritas Tionghoa, maka merekalah yang menjadi sasaran pertama dari kerusuhan ini.
Dimensi pertarungan kekuasaan juga tidak lepas dari kerusuhan-kerusuhan ini. Para pelakunya tahu persis memainkan sentimen ‘anti-Tionghoa’ yang memang sangat lazim (prevalence) dalam masyarakat Indonesia ketika itu. Soeharto dan militer membatasi peranan peranakan Tionghoa hanya dalam ekonomi — mendorong mereka menjadi penguasa bisnis sambil mengutip rente darinya.
Para jendral dan perwira-perwira militer menjadi kaya tanpa bekerja. Para pebisnis Tionghoa mendapatkan perlindungan. Sementara kesempatan berusaha ditutup dari kelas menengah dan rakyat biasa yang tidak punya akses dan tidak mampu membayar para jendral.
Itulah latar belakang kerusuhan sadis yang terjadi 1998. Banyak orang mungkin akan meremehkan korban dari kerusuhan yang jumlahnya hanya beberapa ribu ini. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembantaian 1965.
Namun sadisme dari kerusuhan 1998 ini hampir menyamai 1965. Yang lebih membikin perih adalah bahwa jika 1965 berlangsung di ruang-ruang sunyi yang tidak terjangkau media, maka 1998 terbuka dan menjadi pengetahuan umum. Mayat-mayat terbakar, perempuan-perempuan Tionghoa yang menjadi korban-korban perkosaan, itu semua diungkap ke hadapan publik.
21 Mei 1998 tidak berdiri sendiri. Ia adalah kulminasi dari pertarungan kekuasaan di dalam rejim Orde Baru. Didalamnya adalah pembakaran rumah-rumah ibadah, pemberangusan partai oposisi, kerusuhan-kerusuhan karena ketimpangan ekonomi, penculikan para aktivis demokrasi (sebagian dari mereka tetap hilang hingga kini!), dan perkosan yang terarah dan sistematis terhadap perempuan-perempuan Tionghoa.
Tidak ada satu pun dari perkara ini selesai secara hukum. Tidak ada satu pun dari institusi yang terlibat ini bisa diminta pertanggungjawaban. Tidak ada satu pun dari mereka yang bertarung dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang tidak berdosa ini bertanggungjawab.
Sebagai bangsa relijius, kita selalu mengelak tanggung jawab. Selalu kita katakan, Tuhan yang akan membalas. Sementara, kuburan Soeharto di Matesih, Karanganyar, setiap hari disinggahi ratusan bus untuk berziarah. Ya, orang ngalap berkah dan mendoakan pemimpin yang lalim.
Apa yang kita dapati dari Reformasi ini? Tidak ada! Kekuasaan memang tidak lagi berpusat pada Soeharto. Bahwa kita punya partai-partai politik (sama seperti jaman Orba); kita punya politisi sipil (juga ada pada jaman Orba); tentara tidak lagi di DPR — tapi sekarang mereka dimana-mana; polisi kita sama saja kelakuannya dan bahkan jadi kekuatan politik; semuanya berbeda tapi intinya sama saja.
DPR kita impoten — sama seperti jaman Orde Baru. Rakyat diwakili oleh para artis dan pedagang yang tahu persis bagaimana membeli suara. Bahkan Orde Baru terlihat lebih baik karena terang-terangan mendudukan para penjilat yang kompeten sebagai wakil rakyat.
Keadilan kita hanya untuk para elit — sama seperti jaman Orde Baru. Hukum kita sangat gampang dipengaruhi — sama seperti Orde Baru. Korupsi merajalela dimana-mana — sama seperti Orde Baru. Militer kita makin kuat secara sosial dan politik — apa bedanya dari rejim Orde Baru? Pemerintah daerah kita makin lemah; dan kekuasaan makin tersentralisasi — dengan para elit daerah lehernya sampai patah karena mendongak ke Jakarta — tidak berbeda dengan Orde Baru.
Ekonomi? Berapa persen dari ekspor kita dari industri manufaktur? Selamanya ekonomi kita hanya mengeksploitas sumber daya alam. Karena ini yang paling mudah dikerjakan dan memberikan kekayaan paling cepat untuk para elit. Tidak ada industri manufaktur yang tumbuh. Padahal tidak ada negara di dunia ini yang bisa maju tanpa manufaktur.
Pendidikan? Apakah anak-anak kita makin pintar, seperti anak-anak Vietnam, yang skor PISA mereka berada di 10 besar dunia? Yang lebih menyesakkan adalah angka NEET (Not in Education, Employment, or Training) di kalangan anak muda yang berusia 15-24 tahun yang besarnya 21,36%. Artinya, satu dari lima anak Indonesia dalam usia itu tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, atau tidak sedang menjalani pelatihan untuk satu ketrampilan!
Inikah hasil dari Reformasi? Sistem ekonomi kita semakin menguntungkan yang kuat, yang membeli apa saja — termasuk kekuasaan — untuk bisa tetap kaya. Kita miskin namun merasa kaya. Kampus-kampus kita berisikan orang-orang kaya tanpa ada kesempatan rakyat biasa dan miskin untuk bisa menempuh pendidikan tinggi. Neo-liberalisasi tidak hanya mematikan kesempatan rakyat biasa; namun dosen pada para intelektual kampus pun dipaksa untuk menjadi pengabdi karir dengan beban kerja makin berat dan gaji yang tidak layak.
Dilihat dari kacamata ini, Reformasi adalah revolusi dari Oligarki. Revolusi kaum kaya dan berkuasa. Revolusi yang mengubah sendi-sendi Republik ini dengan menjadikan yang kaya semakin kaya dan berkuasa.
Lihatlah siapa yang berkuasa saat ini? Ia adalah percontohan orang super kaya yang mampu berkuasa karena kekayaannya. Bukankah kemarin kita punya penguasa yang berasal dari jelata? Iya. Tapi ia tidak mungkin bisa berkuasa tanpa dukungan para Plutokrat. Ia hanya semacam ‘decoy’ atau umpan dari para Oligarkh dan ketika berkuasa ia lebih melayani kepentingan para Oligarkh yang melayaninya.
Apakah ada harapan? Saya pesimis. Terutama karena melihat para mantan revolusioner sekarang menikmati hasil Revolusi Oligarki yang dulu mereka tentang setengah mati itu.