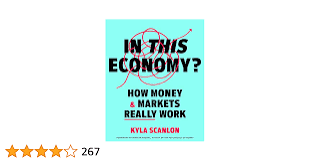Pariwisata sering kali dipasarkan sebagai “Industri Tanpa Asap”. Sebuah narasi yang menempatkannya sebagai sektor yang bersih, estetis, dan penuh sukacita. Namun, di balik brosur mengilap dan filter media sosial yang mempercantik pemandangan, realitas di lapangan kerap menunjukkan wajah yang kontradiktif.
Destinasi wisata yang semula menjadi perlambang keasrian kini perlahan berubah menjadi etalase kerusakan lingkungan. Di sinilah kita berdiri pada sebuah persimpangan krusial, apakah kita sedang membangun warisan alam untuk masa depan, atau justru sedang mencetak timbunan sampah yang akan menjadi beban abadi bagi generasi mendatang?
Di balik gemerlap angka kunjungan wisatawan dan devisa negara, tersimpan luka menganga pada ekosistem yang menjadi jualan utamanya. “Warisan Alam Bukan Sampah” bukan sekadar metafora tentang botol plastik yang berserakan di pantai, melainkan sebuah gugatan ideologis terhadap cara kita memperlakukan bumi, apakah ini adalah warisan yang harus dijaga, atau sekadar tempat pembuangan dari nafsu konsumsi manusia?
Akar masalah dari kerusakan lingkungan di destinasi wisata ini adalah cara pandang antroposentris yang melihat alam sebagai objek. Dalam ekonomi pariwisata saat ini, gunung, hutan, dan laut dikonversi menjadi “produk”. Ketika alam dianggap sebagai produk, maka hukum efisiensi berlaku, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya (perawatan) sekecil-kecilnya.
Mentalitas ini mirip dengan frontier mentality, di mana manusia merasa memiliki hak tak terbatas untuk mengeksploitasi ruang baru. Di Labuan Bajo, Bali, hingga Mandalika, kita melihat bagaimana lanskap alam diubah secara paksa untuk memenuhi standar estetika “instagenic” yang dangkal, sering kali dengan mengorbankan daya dukung lingkungan carrying capacity.
Tragedi Kepemilikan Bersama (The Tragedy of the Commons)
Sampah dalam pariwisata adalah manifestasi dari kegagalan tata kelola. Wisatawan datang membawa ekspektasi dan pulang meninggalkan residu. Masalahnya, infrastruktur pengolahan limbah di daerah tujuan wisata sering kali tidak tumbuh secepat jumlah hotel dan restoran.
Kita melihat fenomena di mana laut menjadi “keranjang sampah raksasa”. Ekosistem terumbu karang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh namun hancur dalam sekejap oleh jangkar kapal atau limbah cair hotel. Di sini, warisan alam yang seharusnya bersifat lintas generasi intergenerational equity dikhianati demi keuntungan jangka pendek satu generasi saja.
Masyarakat Lokal sebagai Benteng Terakhir
Pariwisata massal cenderung meminggirkan peran ini. Warga lokal digiring menjadi buruh kasar di tanah sendiri, sementara kebijakan strategis diambil di meja-meja birokrasi yang jauh dari bau tanah dan laut. Menyelamatkan warisan alam berarti harus mengembalikan kedaulatan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat lokal yang memiliki ikatan batin dengan tanahnya.
Sudah saatnya kita bergerak melampaui “Sustainable Tourism” (Pariwisata Berkelanjutan) menuju “Regenerative Tourism”. Perbedaannya mendasar pariwisata berkelanjutan hanya mencoba mengurangi dampak negatif, sementara pariwisata regeneratif bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan ekosistem yang sudah rusak.
Warisan alam tidak boleh hanya dipandang sebagai aset yang “dijaga agar tidak rusak”, tapi sebagai organisme hidup yang harus disehatkan kembali. Karena itu memerlukan keberanian politik untuk membatasi kuota kunjungan (seperti sistem carrying capacity yang ketat) dan penerapan pajak lingkungan yang tinggi namun transparan penggunaannya.
Menyebut alam sebagai warisan berarti mengakui adanya hak milik generasi mendatang. Setiap butir pasir dan tetes air di destinasi wisata adalah titipan. Jika kita terus memperlakukan destinasi wisata seperti pabrik ekstraktif, maka kita tidak sedang mewariskan keindahan, melainkan tumpukan sampah dan kerusakan permanen. Pariwisata harus berhenti menjadi predator bagi alam dan mulai menjadi pelindungnya.
Dalam diskursus pariwisata arus utama, masyarakat lokal sering kali ditempatkan dalam posisi yang paradoksal. Di satu sisi, keramah-tamahan hospitality, mereka dijual sebagai aset utama dalam brosur wisata. Namun di sisi lain, mereka kerap dituding sebagai aktor di balik kekumuhan dan minimnya standar sanitasi. Tuduhan ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga menyesatkan. Secara historis, keberlangsungan ekosistem di banyak destinasi unggulan justru terjaga berkat praktik kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad.
Masyarakat adat di berbagai penjuru Nusantara memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang sangat ketat. Di Maluku dan Papua, terdapat tradisi Sasi larangan adat untuk mengambil hasil laut dalam jangka waktu tertentu agar ekosistem memiliki ruang untuk pulih. Di Bali, sistem Subak tidak hanya mengatur irigasi, tetapi juga menjaga kesucian bentang alam.
Namun, ketika sebuah wilayah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), logika birokrasi yang bersifat top-down sering kali menggusur hukum-hukum adat ini. Saat ini tuan rumah yang menjadi penonton, Pariwisata massal menjanjikan lapangan kerja, tetapi pertanyaannya pekerjaan seperti apa? Sebagian besar warga lokal hanya diserap sebagai tenaga kerja upah rendah seperti petugas kebersihan, pramusaji, atau buruh konstruksi. Sementara itu, keuntungan ekonomi terbesar mengalir kembali ke pemilik modal besar.
Ketimpangan ini menciptakan gesekan sosial. Ketika harga kebutuhan pokok dan tanah di sekitar area wisata melonjak drastis, warga lokal terpaksa menepi atau bahkan terusir dari tanah kelahirannya (gentrifikasi). Dalam kondisi terhimpit secara ekonomi, sulit mengharapkan masyarakat memiliki energi untuk memikirkan pelestarian lingkungan jika pemenuhan kebutuhan dasar mereka saja terancam oleh industrialisasi pariwisata.
Banyak desa wisata yang kini terjebak dalam “teater budaya”. Ritual yang dulunya sakral kini diperpendek durasinya dan disesuaikan jadwalnya demi memuaskan paket tur. Hubungan antara manusia dan alam yang bersifat spiritual kini bergeser menjadi transaksional. Ketika budaya hanya dipandang sebagai atraksi, maka tanggung jawab moral terhadap alam yang terkandung dalam budaya tersebut juga ikut memudar.
Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) Menyelamatkan “Warisan Alam” berarti harus menempatkan masyarakat lokal bukan sebagai objek pelengkap, melainkan sebagai subjek utama pengambil keputusan. Model Community Based Tourism (CBT) yang sejati harus mampu memberikan kendali penuh kepada warga untuk menentukan kuota wisatawan yang boleh masuk dan bagaimana cara mengelola limbah di wilayah mereka.
Tanpa adanya kedaulatan ruang bagi penduduk asli, upaya konservasi hanya akan menjadi proyek kosmetik. Karena sesungguhnya masyarakat lokal adalah garda terdepan jika mereka sejahtera dan dihormati hak-haknya atas tanah dan tradisi, maka alam akan terjaga dengan sendirinya tanpa perlu paksaan regulasi yang kaku.
Sebagai penutup dari opini yang bertajuk “Warisan Alam Bukan Sampah” adalah sebuah peringatan keras bahwa arah pariwisata Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Kita tidak bisa terus-menerus memuja angka pertumbuhan kunjungan jika di saat yang sama kita membiarkan pondasi ekologis dan sosialnya runtuh. Karena itu alam harus dipandang sebagai:
Pertama, alam harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk pulih, bukan sekadar komoditas ekstraktif. Menyebutnya sebagai “warisan” berarti ada tanggung jawab moral untuk menyerahkannya kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik, bukan dalam bentuk residu kehancuran.
Kedua, kedaulatan agraria adalah kunci. Konflik lahan di destinasi wisata membuktikan bahwa pembangunan yang mengabaikan hak masyarakat lokal adalah pembangunan yang rapuh. Tanpa kepastian hak atas tanah bagi warga asli, pelestarian lingkungan hanyalah jargon kosong. Masyarakat lokal bukan hambatan investasi tapi mereka adalah benteng terakhir pelestarian alam.
Ketiga, transisi ke pariwisata regenerative yakni paradigma Sustainable Tourism (hanya mengurangi dampak buruk) sudah tidak lagi cukup. Kita butuh Regenerative Tourism sebuah model di mana setiap dollar yang masuk dari turis harus berdampak langsung pada pemulihan ekosistem dan penguatan kapasitas ekonomi warga lokal secara berkeadilan.
Keempat, intervensi negara yang berpihak yakni pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer demi lingkungan, seperti pembatasan kuota wisatawan carrying capacity yang ketat, audit lingkungan menyeluruh terhadap hotel-hotel besar, dan penghentian pemberian izin di wilayah-wilayah konflik agraria yang belum terselesaikan.
Karena itu kita harus memastikan bahwa pariwisata seharusnya menjadi jembatan kebudayaan dan konservasi, bukan mesin penghancur ruang hidup. Jika kita gagal membenahi paradigma ini sekarang, maka anak cucu kita kelak hanya akan mewarisi narasi tentang keindahan masa lalu di atas tumpukan sampah dan beton yang tak lagi bernyawa.